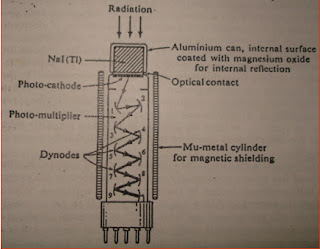A. Photograph
Photograph merupakan suatu gambar (foto) dari sebuah obyek yang dibuat dengan menggunakan kamera dan film. Dewasa ini seni photografi banyak digeluti oleh masyarakat yang memiliki hobby untuk mengabadikan gambar real ke dalam sebuah kertas. Dimana gambar yang diharapkan sama persis dengan aslinya namun dalam ukuran yang lebih kecil.
Pada jaman dahulu, orang membuat gambar dengan menggunakan pewarna dan kanvas, namun sekarang dengan ditemukannya kamera, kegiatan bisa didokumentasikan dengan sangat baik dan tidak menyita banyak waktu. Dimana kejadian atau peristiwa tersebut dapat direkam apa adanya
Saat ini ada dua jenis kamera yang digunakan untuk membuat foto, yaitu kamera digital dan kamera non digital. Kamera digital merupakan kamera dengan seperangkat alat berteknologi canggih yang mampu menyimpan data ataupun gambar dalam sebuah memory, dimana gambarnya pun dicetak dengan menggunakan printer sehingga hasilnya lebih memuaskan daripada kamera biasa.
Sedangkan kamera non digital merupkan jenis kamera konvensional yang menggunakan film sebagai tempat untuk merekam obyek yang nantinya diteruskan ke dalam kertas foto untuk dicetak. Adapun proses pembuatan gambar dari kamera non digital akan diuraikan lebih jelas di bawah ini.
B. Foto Hitam Putih
Film negatif atau klise, adalah sebutan untuk citra yang terbentuk pada film sesudah dipotretkan dan sesudah dikembangkan, di mana bagian yang terlihat gelap pada gambar, pada objek terlihat terang. Warna yang timbul berlawanan karena bagian terang dari objek memantulkan banyak cahaya ke film dan menghasilkan area gelap
Film pada foto hitam putih merupakan emulsi perak halida (biasanya bromida, AgBr) dalam gelatin. Pada proses pembuatan gambar hitam putih, jika film terkena cahaya, butiran perak bromida teraktifkan sesuai dengan tingkat cahaya yang mengenainya. Film yang telah terkena cahaya bila dimasukkan ke dalam larutan pengembang pereduksi lemah misalnya metol, amidol atau hidrokuinon C6H4(OH)2, butir perak bromida teraktifkan membentuk perak logam yang hitam. Semakin kuat intensitas cahaya, perak logam hitam yang terjadi semakin banyak. Begitu pula sebaliknya, Semakin lemah intensitas cahaya maka perak logam hitam yang terbentuk sedikit.
Apabila film/ kertas foto terkena cahaya, akan terjadi reaksi :
AgBr -----> AgBr*
Tanda * menyatakan AgBr tereksitasi oleh cahaya. Apabila film yang telah digunakan dan terkena cahaya tersebut dicuci dalam larutan pengembang (developer), akan terjadi reaksi :
2 AgBr *(s) + C6H6O2 (aq) -----> 2 Ag(s) + 2 HBr(aq) + C6H4O2
Cairan pengembang C6H6O2 (hidrokuinon), dalam hal ini bertindak sebagai zat pereduksi. Jadi dalam reaksi itu terjadi proses reaksi redoks.
Oksidasi :
C6H6O2 (aq) ------> C6H4O2 (aq) + 2 H+ + 2 e
Reduksi:
2 Ag+ + 2 e -----> 2 Ag (s)
Di samping hidrokuinon, dalam larutan pengembang perlu ditambahkan metol (N-metil-p-aminofenol sulfat). Metol berfungsi sebagai zat superaditif, yang efeknya tidak dapat digantikan dengan memberikan jumlah yang berlebih pada hidrokuinon yang sudah ada. Metol ini bertindak sebagai zat pereduksi juga. Aktivitas hidrokuinon dapat dipacu dengan menambahkan sedikit phenidone (1-phenyl-3-pyrazolidinone). Karena larutan pengembang/developer ini bekerja efektif pada lingkungan basa, maka kita perlu mencampurkan larutan kalium karbonat (atau natrium karbonat) sebagai aktivator untuk memperoleh lingkungan basa dengan pH 9,5 - 10,5.
Cara kerja cetak film hitam putih
Film dipasang di bawah enlarger, lalu cahaya 100 watt dinyalakan. Akan tampak bayangan film itu di atas kertas. Kalau bayangan itu sudah tepat, matikan lampu dan ganti kertas dengan kertas cetak foto. Nyalakan kembali lampu selama sekian detik. Kertas foto kemudian dicelupkan pada larutan pengembang selama beberapa menit. Angkat, kemudian ganti celupkan ke dalam larutan stop batch untuk menghentikan reaksi.
Selanjutnya kertas foto itu dicelupkan pada larutan fixer, lalu kertas foto dibilas dengan air mengalir. Jadilah sebuah foto yang indah, yang kualitasnya bergantung pada lama pencahayaan, jauh dekatnya film dengan kertas foto, waktu pencelupan, kualitas kertas foto, pembilasan, dan sebagainya.
Proses penetralan
Setelah film dicelupkan pada larutan pengembang, maka tahap berikutnya adalah tahap penghentian reaksi sekaligus menetralkan sifat basa yang berasal dari larutan pengembang. Caranya dengan mencelupkan kertas/film pada larutan asam asetat yang telah diberi larutan sodium sulfat untuk mencegah adanya efek swelling. pH larutan dijaga pada kondisi 4 - 5,5.
Proses fiksasi
Logam perak hitam yang terbentuk menghasilkan bayangan film. Agar bayangan film melekat pada film maka harus difiksasi (diikat). Pengikat (fikser) yang umum dipakai adalah natrium tiosulfat. Fiksasi juga bertujuan melarutkan perak bromida yang tidak tereduksi menjadi perak (kalau tidak dihilangkan, jika kertas foto terkena cahaya, akan timbul bayangan hitam tambahan.
Pada proses pengikatan terjadi reaksi sebagai berikut : AgBr(s) larut dalam larutan fikser terbentuk ion perak kompleks.
AgBr(s) + 2 S2O32- -----> [Ag(S2O3)2]3- + Br1-
Proses pembilasan
Tahap akhir setelah fixing adalah pembilasan dengan guyuran air mengalir supaya terbentuk bayangan yang permanen. Proses pembilasan ini bertujuan membuang kompleks perak tiosulfat dan ion tiosulfat. Jika ion tiosulfat masih tertinggal pada film/ kertas foto, maka zat ini akan bereaksi dengan perak yang sudah terbentuk foto/ gambar, sehingga bayangan foto akan menjadi kecoklatan/ kekuningan karena akan terbentuk noda-noda perak sulfida. Jadi pembilasan dengan air yang mengalir itu sangat perlu supaya kualitas foto/ gambar menjadi baik.
S2O32- + 2 Ag -----> SO32- + Ag2S
Hasil dari proses ini adalah gambar dengan berbagai nuansa hitam putih di atas seluloid yang kita kenal dengan negatif film. Dari negatif dibuat foto dengan jalan mencetak pada selembar kertas foto. Bagian hitam pada negatif menghasilkan gambar putih pada foto sedangkan bagian putih pada negatif menghasilkan gambar hitam pada foto. Disebut negatif film karena gambar yang tercetak berlawanan dengan filmnya.
Kira-kira hanya 25 % perak bromida yang menjadi perak logam hitam dari perak bromida seluruhnya, sisanya sebanyak 75% larut bersama fikser. Jika fikser telah jenuh dengan perak, maka larutan ini tidak dapat dipakai lagi. Harus diganti dengan yang baru. Larutan jenuh tersebut menjadi limbah utama laboratorium cuci cetak foto. Limbah dengan kandungan perak 75% tidak boleh dibuang sembarangan karena logam berat Ag akan mencemari lingkungan. Oleh karena itu limbah ini dapat dimanfaatkan untuk penyepuhan perak. Kandungan ion perak yang cukup besar dalam larutan diambil dengan cara elektrolisis. Yang menjadi masalah adalah tidak semua logam Ag terambil sehingga perlu dilakukan penelitian lanjut mengenai kondisi optimum seperti suhu larutan, pH dan lamanya elektrolisis.
C. Foto Berwarna
Proses pembuatan foto berwarna tidak jauh berbeda dengan pembuatan foto hitam putih antara lain pemilihan film, pemotretan hingga cuci cetak.
Dalam mempelajari fotografi berwarna kita berpegang pada pengertian:
- Cahaya putih baik yang datang dari matahari yang akan merangsang perakhalida film berwarna, maupun dari lampu alat pembesar yang akan merangsang perakhalida kertas foto berwarna, terdiri dari kombinasi tiga cahaya berwarna yaitu: biru, hijau, dan merah.
- Emulsi yang terdapat pada film berwarna maupun pada kertas foto berwarna terdiri dari tiga lapis yang masing-masingnya mengandung perakhalida yang dapat merekam cahaya biru, hijau, dan merah.